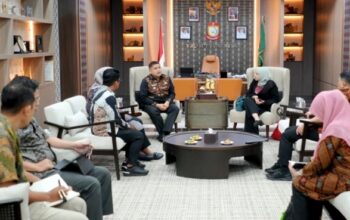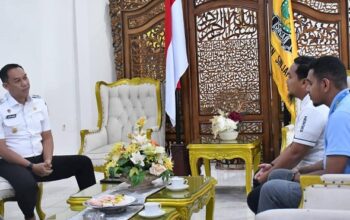KETIDAKSIAPAN budaya dan sosial dalam menyerap perubahan cepat adalah fenomena kompleks yang muncul ketika transformasi digital bergerak jauh lebih cepat dibanding kemampuan masyarakat untuk memahami, menginternalisasi, dan menyesuaikan diri secara kultural. Kondisi itu membutuhkan pendekatan guna mengatasinya.
Teknologi tidak hanya mengubah cara individu bekerja, belajar, atau berkomunikasi, tetapi juga mengguncang tatanan nilai, norma, dan pola interaksi sosial yang sudah lama menjadi landasan kehidupan bersama.
Dalam konteks Indonesia, di mana ruang kebudayaan masih banyak bergantung pada relasi lisan, tatap muka, dan kedekatan emosional, perubahan digital yang bersifat instan dan serba daring menciptakan jarak baru antara manusia dengan lingkungannya.
Perubahan cepat itu memunculkan fenomena cultural shock atau kejutan budaya digital, ketika masyarakat merasa ketinggalan, tidak siap, atau bahkan terintimidasi dengan kecepatan informasi dan modernisasi.
Tradisi yang biasanya berjalan melalui proses kontemplatif dan pewarisan nilai antar generasi kini berhadapan dengan budaya viral yang menuntut respons instan, modifikasi cepat, dan orientasi pada tren.
Hasilnya adalah hilangnya ruang reflektif dalam kehidupan sosial; budaya kini direduksi menjadi konten yang dapat dikonsumsi, dipermainkan, dan dilupakan dalam hitungan detik.
Ketidaksiapan itu juga tercermin dalam menurunnya penghormatan pada norma sosial tradisional (kearifan lokal). Pola komunikasi digital yang bebas dan tanpa mediator sering berbenturan dengan nilai sopan santun, tata krama, dan hierarki sosial yang selama ini menjadi perekat interaksi masyarakat Indonesia.
Misalnya saja, kelompok muda dengan identitas digital baru sering dianggap “kurang ajar” (tidak sopan) atau tidak menghargai otoritas karena komunikasi daring tidak mengharuskan ritual hormat sebagaimana percakapan tatap muka. Perbedaan itu menimbulkan kesenjangan generasi yang semakin melebar.
Secara sosial, teknologi menghasilkan fragmentasi komunitas. Pola lama berbasis gotong royong, musyawarah, dan ruang publik fisik digantikan oleh komunitas-komunitas virtual yang cair dan tidak permanen (walau tidak saling kenal).
Di satu sisi, komunitas digital memungkinkan pertemuan lintas wilayah, tetapi di sisi lain mengikis kedalaman relasi karena interaksi berlangsung secara dangkal, cepat, dan sering kali tanpa tanggung jawab moral.
Masyarakat kehilangan ruang untuk membangun empati karena kedekatan emosional tidak lagi berakar pada pengalaman konkret bersama, mereka terbentuk oleh ‘motor penggerak’ bernama algoritma, sadar atau tidak semua berjalan seperti wajar.
Ketidaksiapan budaya juga tampak dalam cara masyarakat menyikapi perubahan nilai yang datang dari luar. Media digital membawa masuk budaya global melalui simbol-simbol gaya hidup, bahasa, dan hiburan.
Tanpa penyaringan, masyarakat, terutama generasi muda, dapat meniru tanpa memahami konteks budaya asal maupun kesesuaian dengan nilai setempat.
Akibatnya, terjadi erosi identitas kultural, ketika referensi nilai lebih banyak dibentuk algoritma global daripada kearifan lokal.
Kritik penting lainnya adalah bahwa negara dan lembaga sosial tampak kurang responsif dalam merancang mekanisme adaptasi budaya yang sehat. Kurikulum pendidikan, lembaga adat, dan media arus utama belum cukup aktif menjembatani perubahan nilai antara era tradisional dan era digital.
Ketika negara hanya fokus pada pembangunan infrastruktur digital tanpa membangun ekosistem kebudayaan yang siap menyerap perubahan, maka masyarakat dipaksa menyesuaikan diri sendirian, sering kali dengan trauma, kecemasan, atau kebingungan identitas.
Di tingkat mikro, ketidaksiapan sosial ini memunculkan fenomena psikososial seperti meningkatnya kesepian, alienasi, dan keresahan sosial. Orang mungkin merasa selalu terhubung secara digital, tetapi terputus secara emosional.
Hubungan keluarga menjadi renggang karena nilai kebersamaan digantikan oleh kesibukan masing-masing dengan gawai. Komunitas yang dulu saling menopang kini kehilangan energi solidaritas karena interaksi virtual tidak menghasilkan rasa keterikatan yang sama.
Pada akhirnya, ketidaksiapan budaya dan sosial dalam menyerap perubahan bukan semata-mata kegagalan masyarakat tradisional, tetapi juga kegagalan sistem dalam menyediakan jembatan transisi yang manusiawi.
Transformasi digital idealnya bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi proses kultural yang membutuhkan pendampingan, refleksi kritis, pendidikan nilai, dan ruang dialog antargenerasi.
Tanpa itu semua, perubahan digital hanya akan melahirkan kemajuan teknis, namun meruntuhkan fondasi sosial dan budaya yang menjadi identitas suatu bangsa. Kita belum sepenuhnya terlambat, merancang kembali ekosistem digital berbasis kearifan lokal adalah peta jalan menuju kemaslahatan hidup masyarakat Indonesia di abad ini.
*) Dr Zulkarnain Hamson, SSos MSi, Akademisi Komunikasi Berdiam di Makassar